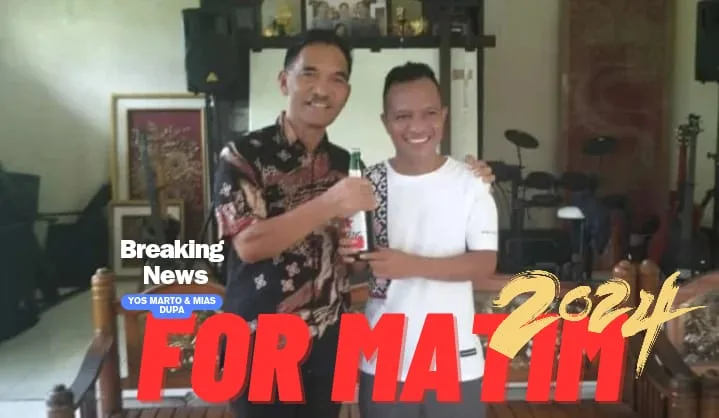Exefer Joak-im
Dari Kaki Gunung Ranaka
Sabtu di ujung hari, saat hendak berpulang ke kamar, berbagi segelas kopi adalah alasan yang nikmat untuk menyulam kenanganan dengan tetangga-tetangga kamar. Jaring-jaring kisah akan dengan sendirinya terhubung bila diucapkan. Mungkin ini menjadi cara istimewa mendulang gembira, menertawakan konyolnya diri, melampiaskan amarah dan rasa kecewa.
Pada moment ini, tanpa disadari aku hanyut termenung dan diantar kembali pada tanggal 10 Agustus, 9 tahun silam. Seorang pastor menerima kedatanganku dan rekan-rekan anggota baru. Wajah polos dan aroma liburan jelas tergambarkan dari penampilan. Aku berdiri dalam kerumunan dan mendengarkan sambutan selamat datang dari seorang pria usia 50-an. “Kamarnya pas untuk seorang. Berukuran 3×2 meter. Diisi dengan sebuah tempat tidur, lemari pakaian, bangku, meja, salib, dan rak buku. Selain dari itu, silahkan tambah sendiri.” Akhir dari sambutan itu. Sambutan ini mungkin menjadi sambutan turunan yang akan terus diwariskan.