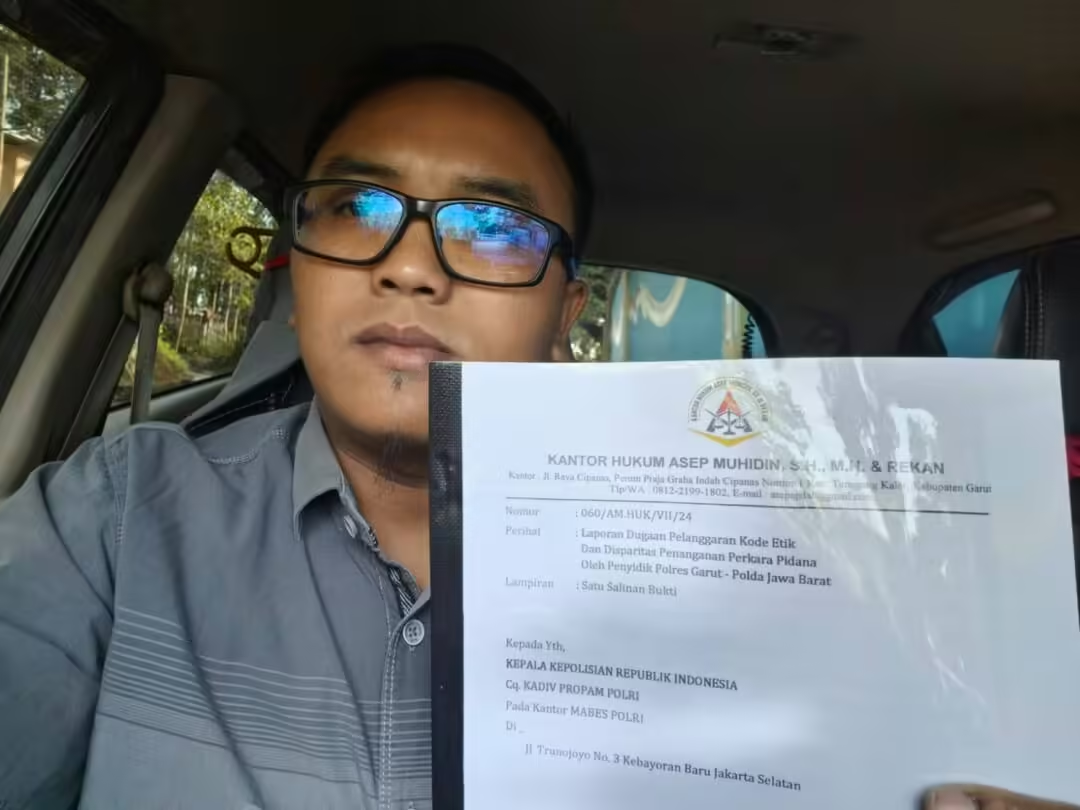Asumsinya, ada sebuah cerita. Terdengar, tak samar, politisi membahas perihal ideologi. Tentang ideologi partai politik (parpol). Pada bagian ideologi parpol, bukannya membahas intisari ideologi politik parpolnya, malah yang terjadi adalah fitnah dan stimatisasi parpol lain. Beberapa parpol yang disebut, dikaitkan melekat dengan “komunisme”.
Itu salah satu trik kampanye politik caleg menuju Pileg 2024. Sebut saja dia adalah oknum politisi. Oknum itu politisi Machiavellian: menghalalkan segala cara untuk menang. Ia tampak cemas, tapi seolah-olah masih berdaya. Mungkin masih ada sisa kekuatannya untuk menyelamatkan diri. Persis orang tenggelam, terpaksa merebut apa saja yang mengapung di atas atas. Kalau-kalau, seonggok kotoran banteng bisa menyelematkannya.
Demikianlan sekilas eksposisi atas ilustrasi oknum politisi yang gemar “political bullying”. Tampaknya, mulut lebih kekar dari kepala. Jadi, apa saja yang melintas di otak, bocor di mulut. Tanpa ada saringan argumen rasional. Gumpalan sentimen dan emosionalnya sudah menumpuk. Itu menumpulkan pikiran bernas dan etika politik.